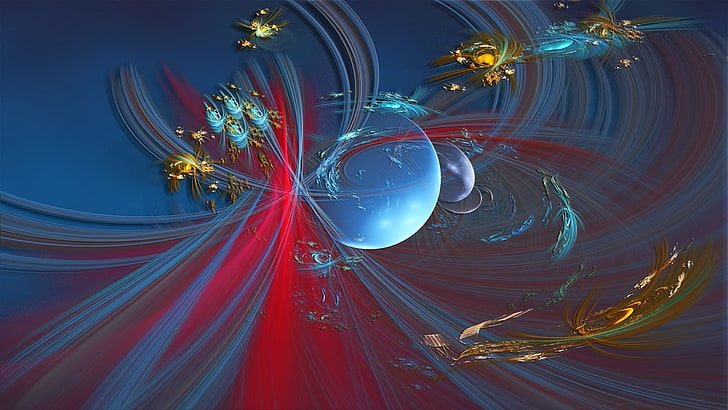Penulis: Tasya D. Amalia*
Mentari terlelap dikaki langit, semburat jingganya meredup terbawa mimpi. Nampaklah bulan datang untuk meronda. Kupandangi lekat sinarnya, terhalang tirai kabut sendu malam. Seandainya ia tak pergi menjauh, pasti tak akan ada yang menyulut api di hatiku. Gejolak baranya menyita seluruh perasaan sayang, perasaan kasih antara buah hati dan penerangnya. Dhamar kunyalakan di atas mimbar lemari bambu buatanku sendiri.
Kupandang lekat api yang berkobar di atasnya. Bergoyang diantara anginmalam yang menebar hawa dinginnya. Kurasakan pipiku basah menyesap relung dada. Entah mengapa seluruh nadiku melambat. Gemuruh di luar sana bahkan mengiringiku pada nestapa. Lagunya serasa menyayat batinku yang membeku. Aku mulai tak mengenal diriku sendiri. Terkadang aku merasa bagai seonggok daging manusia, dan kini yang tersisa hanya butirang debu.
Sudah lama kuingin terlelap dikala malam datang, sudah lama mata kelelahan menahan tangis. Tubuhku hanya bergerak diam ranjang sutera yang kupakai serasa bagai barisan paku tajam. Menancap tubuhku menuju kesakitan. Sudah cukup, aku penat. Penantianku seperti takkan berakhir. Aku berusaha lari dari cengkraman nestapa. Tapi ia menarikku dengan tali airmata. Penglihatanku menari di sekitar.
“Adakah yang bisa membantuku? Tolonglah… asapnya semakin tebal!” teriakku cemas. Kupotong tali air mata itu dengan sebilah tanganku, lalu melangkah berat membuka pintu. Seketika angin liar membelai wajahku. Entah mengapa selanjutnya hatiku padam. Kubalikkan badan melihat kebelakang.
“Ranjang itu terbakar” teriakku.
Asapnya menghitam, kulihat orang di dalamnya terbatuk-batuk. Napasnya terengah-engah menghilang.
“Sudah kubilang asapnya makin tebal, kan? Kenapa diam? Cepat pergi!” Mereka beradu pandang, aku gemetar melihat asap itu kini mencekik salah satu diantaranya. Namun, mereka bersikeras untuk diam. Satu orang matilah sudah.
“Astaga asap itu pembunuh, hentikan…!” Aku terus meneriaki mereka. Tak ada siapapun yang bisa membantuku, mereka semua di dalam. Akhirnya pikiranku melayang pada bulan, kuhampiri ia.
“Mana bintang?”
“Sakit” jawab bulan tanpa melihat padaku.
“Hah..?”
“Seseorang merindu terlalu” Dengan tetap tanpa melihat padaku.
“Hah…aku sungguh khawatir…”
“Aku tahu!”
“Aishh…” teriakku.
“Husss… jangan berisik! Bintang sedang istirahat” Kulihat tikar hitam yang kosongan. Benar adanya tak ada cahaya selain dari Bulan, bahkan cahayanya sendiri tinggal lima watt saja.
“Laila…kau mencariku” ucap bintang. Sontak aku menengok ke atas. Ia tengah berselimut malam tebal.
“Yes… bintang hadir. Tolong aku…! mereka terbunuh di sana”
“Kau, kan punya” Seru bulan mengadu.
“Diam bulan! aku tak bicara padamu… tolong jangan buat bintang keliru”
“Uhuk…uhuk… yang dikatakan bulan benar.”
“Maksudnya? Punya apa?” Bintang menyusup di liur bibirnya. “ Api itu. Seharusnya api itu tidak ada”
“Api apa?”
“Rindu…” aku terperangah. Sedikit tergunjang mendengar perkataannya. Jika benar begitu berarti semua ini karenaku.
“Benar” jawab bulan seolah dapat membaca mendengar kata hatiku.
(baca juga: Pesan Harmoni dari Santri untuk Kebhinekaan Indonesia melalui Sastra)
“Asap itu tercipta dari tetesan air matamu. Tidakkah kau menyadari bahwa rindumu terlalu hingga dapat membunuh mereka.”Api menyulut bara di hatiku lagi. Berkobar merayakan kekalahanku. Bintang mendekat dengan sinarnya yang semakin terang. Kurasakan api itu mengecil.
“Bunuh rindumu… ingatlah bahwa nasi telah menjadi bubur. Ayahmu takkan pernah kembali. Cukuplah api itu saja. Gunakan rindumu untuk merangkul mereka. Mereka membutuhkanmu. Untuk kau tahu saja, penyebab kesakitanku adalah mendengar keluhan mereka padaku. Aku harus mengeluarkan tenaga lebih untuk menenangkan mereka. Kinipun api itu telah tumbuh di hati mereka. Bayangkan jika mereka bernasib sama sepertimu! Yang sebenarnya adalah asap pembunuh itu adalah tangan kananmu, tentu ia pasti patuh padamu”
Bibirku tersekat di tenggerokan. Asumsiku menyalahi aturan kehidupan. Aku kembali dengan tertunduk malu. Langkahku terasa hampa. Di depan pintu rumah aku berhenti. Terlihat asap hitam menari-nari dihadapanku,
“Berhenti tuan asap! Bebaskan keluargaku” mendengar perkataanku ia terkejut, namun tanpa membantah ia bergerak rancu.
“Kumohon… pulanglah!” gumamku pasrah. Tak berani kutengadahkan wajah menyadari kebodohanku selama ini. Kecewa menarik asap untuk pergi. Mereka yang terbunuhpun hidup kembali seolah tak terjadi apa-apa. Perkataan bintang camcuk kesadaranku. Senyum kusebar pada benih tanah keluarga. Bunga kebahagiaan merekah disisi dinding bersama. Meski terkadang aku akan tetap merindu. Mengunci rapat-rapat pintu dan menangis tersedu-sedu. Membiarkan asap menyelimuti dan membebaskannya untuk membunuh dengan mencekikku. Setidaknya aku akan terlelan sampai esok pagi menjelang. Ajaibnya, aku akan hidup kembali. Menyenangkan menjadi orang yang mati suri beberapa kali. Baik aku, api ataupun asap pembunuh tak ada yang tahu darimana semua ini berawal. Yang kami tahu saat ini adalah bahwa kami berteman baik dan akhirnya aku tahu ayahku memang telah pergi. Selamanya.Berat memang namun harus tetap disyukuri.
Aku, api dan asap pembunuh. Pada penghujung malam kami bersatu. Dan aku entah bagaimana tak dapat merasakan napasku lagi. Perlahan hilang dan kandas. Aku…
Jember, selasa 05/06/18
Di mana kini tak ada aku, api dan asap pembunuh
-Kedamaian-
*Penulis adalah alumni SMA Nuris Jember berprestasi nasional di ajang Ceris Kemenag tahun 2018, kini sedang menempuh studi sarjana di Universitas Negeri Malang