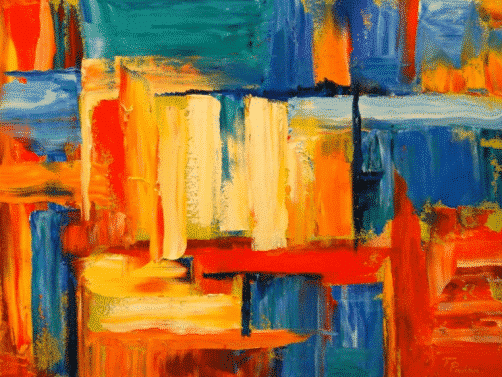Penulis: Ayu Novita Sari*
Siapa kau?
Berdiri meringis, di atas tangis
Kau tak tahu siapa aku
Kau taburkan mawar dalam mimpi
Aku berdarah
Terkapar dalam diam
Dan kau …
Dengan tubuh terlentang, mencoba tenang
Embun berhamburan mencari tempat bertapa. Setitik embun tak sudi menjatuhkan tubuhnya pada tanah pagi yang retak. Ia menyelubung pada tubuh daun yang bergantung lemah. Embun itu mencemaskan tubuhnya. Ia melihat embun yang lain hangus setelah bersetubuh dengan tanah. Tangan-tangan mungilnya memegang erat ranting yang perlahan mulai rapuh. Daun yang sebelumnya ia pijak terbang tergeletak dan akhirnya terbakar. Kegelisahannya memuncak, terdengar suara desauan angina yang meracaui nasib embun.
“Untuk apa Kau masih di sini?.” Tiba-tiba suara seseorang menggelegarkan di balik tubuh embun.
“Karena aku tak ingin hilang sia-sia.” Celoteh embun. Seekor semut hitam mendekati posisinya.
“Bukankah hidupmu memang sesaat. Datang di pagi hari dan hilang diterpa sinar matahari, apa bedanya dengan hari ini?”
“Kau tak mengerti hidupku. Aku tidak hilang tetapi aku meresap dalam tanah yang baik untukku bertapa. Bukan tanah yang menghanguskanku .”
Jlepp … .
Tubuh mereka bergerak merasakan getaran. Ranting yang mereka pijak angkat bicara.
“Apa yang Kau harapkan? Berharap merasa aman dengan bersemayam dalam rantingku. Tidak, bahkan lebih parah hidupku tinggal menunggu mesin pembunuh atau lapuk karena terbakar. Tidak ada tempat aman di sini.”
Awan tak memunculkan batang hidungnya, memilih kea rah utara dan selatan demi melangsungkan hidup. Langit menyisakan biru dan kicauan burung kelaparan. Gelegar suara bising, menyakitkan telinga. Setitik embun yang resah itu terjatuh pada sela-sela tanah yang kering. Ia melihat pohon yang tadi ia tumpangi tumbang terlilit mesin yang entah apa namanya. Pohon itu melambaikan ranting rapuhnya pada embun cemasitu. Terlihat mimik wajah pasrah dalam lekukannya.
Dengan sisa tenaganya ia mengendap menyelinap di sela-sela retakan tanah gersang. Tak jauh dari langkahnya ia menemukan cacing tanah yang terkapar lemas kekurangan cairan. Ia juga melihat akar-akar tunggang dan serabut menjadi serpihan. Ia balut tubuh cairnya dengan sisik ular yang di tinggal mati pemiliknya. Terus berjalan entah berapa meter ia mengalirkan tubuhnya.
(baca juga: Sisihkan Ribuan Peserta, Cerpen Ayu Novita Sari Masuk Antologi Nasional)
Di sebuah tempat yang entah bernama apa, ia menemukan cangkang siput yang berlendir yang lumayan membuat tubuhnya mendingin. Ketika ia senderkan tubuhnya ke cangkang terdengar suara gemuruh di atas tanah. Tergeraklah cangkang yang ia senderi. Embun terhempas tidak terlalu jauh dengan cangkang yang ia senderi tadi, ia melihat sesuatu mulai perlahan keluar dari dalam cangkang. Benar saja seorang siput tua menampakkan batang hidungnya.
“Kau tersesat nak?” Siput tua itu tergerak ke atas melewati lorong-lorong membawa cangkangnya. “Ini adalah tempat yang salah. Tidak sepantasnya embun lembut sepertimu, mengelus tanah retak yang munafik ini.” Setitik embun itu tertarik dengan pembahasan ini. ia menarik dirinya mengikuti langkah siput tua itu.
“Maksud Kakek?” Rupanya pertanyaan itu yang memang pantas untuk dipertanyakan. Siput tua itu tetap diam dalam saktanya. Setitik embun itu tertatih mengikuti siput tua itu. Matahari rupanya sedang meradang sekarang, sinarnya tak ada yang meresap memantul kesana kemari tanpa arah. Setitik embun itu mulai merasakan lemas pada tubuhnya. siput tua itu mengetahui permasalah yang ia alami, dengan sigap ia menempelkan lendir untuk menambah cairan pada setitik embun itu.
Angin mengalihkan haluannya. Tak ada angin maupun udara di alam bagian ini.
“Kau lihat rumput lemah itu.” Setitik embun itu mengomando pandangannya pada sesuatu yang ditunjuk oleh siput tua itu. “Dia sendiri sekarang, hanya dia yang ingin berjuang mempertahankan hidupnya. Semua keluarga kerabatnya hancur hilang bahkan entah dibawa kemana.” Siput tua itu melangkah perlahan di atas tanah yang berwarna coklat dan panas, setitik embun itupun mengikuti dengan perlahan.
“Lihat juga batang pohon yang terbakar itu.” Asap berhasil menghalangi pandangan setitik embun tetapi dengan meneliti ia menilik sebatang pohon berteriak di tengah kobaran api.“ Dulu ia dan keluarganya tempatku mencari makan dan mencari kedamaian. Tetapi dunia yang lain tak menyukai kita ada disini. Mereka merampas semua keluarganya, dan membuang dirinya yang cacat hanya karena ia menyimpan rayap dalam tubuhnya.”
Langit sedang bermimpi akan tanah yang dicuri kebebasan. Tanah habis terbakar kepakan sayap burung yang menyaup-nyaup tenggelam di bagian bumi lain. tanah yang kecil meminta kedamaian. Ada sebatang hati kecil yang sedang menangis. Membuai mimpi-mimpi yang selalu dipertanyakan.
“Aku kehilangan semuanya. Bahkan aku akan kehilangan diriku sendiri. Sebelum itu aku tidak ingin kehilangan generasi muda sepertimu.” Siput tua itu menyenderkan tubuhnya pada batu yang pasrah.
“Kau tahu kenapa aku turun ke bumi?” Setitik awan itu duduk di sebelah siput tua. “ Karena mereka yang di atas ingin melihat tanah bahagia. Tetapi apa? Tanah tak menerimaku dengan semestinya. Aku menyesali takdirku. Aku sudah berabad-abad tak ingin jatuh tetapi pagi itu adalah embun terakhir untuk bumi. Dan aku adalah embun terakhir.”
Debu mendesir menyisir dengan teriakan akan kematian mereka. Raungan akan permintaan kedamaian menggebu. Tak ada suara. Sepi.
“Saya akan kembali ke langit kek. Tetapi saya tak tau bagaimana caranya.”
Siput tua itu mendesah.
“Sudah terlambat nak, jangan menyianyiakan waktu meratapi akan mimpi-mimpimu tentang dunia di atas sana. Kau sudah di takdirkan memperjuangkan bumimu ini.”
Embun beranjak berdiri mencari sesuatu yang memungkinkan memberi pemahaman akan usahanya. Ia meraih batang kayu mungil.
“Saya hanya membutuhkan air.”
“Ini hutan bukan lautan.” Setitik embun itu mulai geram. Ia tak ingin mati sia-sia di tempat yang munafik ini.
“Tapi Kek!.” Ia melihat siput tua itu masuk pada cangkangnya. “Kek … Kek ..?” Tak ada jawaban. Ia masuk melalui celah cangkang yang retak. Berhasil melakukannya terjadi gemuruh di luar sana ia mengintip lewat celah yang berlubang itu. Gelap.
Wahai semesta. Tanahku kandas, dicuri kebebasannya. Langit kami sedang meratapi akan mimpi. Dimana kipasan sayup-sayup burung senang?. Tanah kecil ini memiliki hati kecil yang sedang menangis mengemis. Kami masih di buaian mimpi.
Selepas dari abad itu aku mengembun di suatu tempat yang tak kukenali. Panas dan mendidih.
“Berikan aku kedamaian dan kesempatan!.”
Agustus 2018
Tertoreh di
Jembatan layang.
*Penulis adalah alumni SMA Nuris Jember, berprestasi nasional, penulis buku antologi cerpen “Gandrung Melarung Mendung”, kini sedang studi sarjana di FIB UNEJ